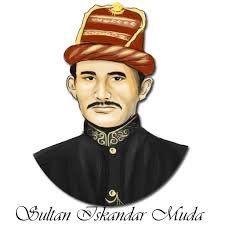Riuh di Lapangan Tengah Kota
Pagi itu, Blang Padang kembali ramai. Anak-anak berlarian di jalan setapak, para lansia berjalan santai menghirup udara segar, sementara pedagang kecil sibuk menawarkan jajanan tradisional. Bagi warga Banda Aceh, lapangan luas ini bukan sekadar taman kota—ia adalah denyut kehidupan, tempat pertemuan sosial, ajang olahraga, hingga ruang perayaan budaya.
Namun, di balik riuhnya aktivitas harian, sebuah pertanyaan besar menggantung: milik siapa sebenarnya Blang Padang?
Jejak Sultan Iskandar Muda
Sejarah mencatat, Sultan Iskandar Muda (1607–1636) pernah membeli lahan sawah rakyat di kawasan ini. Lalu, dengan niat ibadah, beliau mewakafkannya untuk Masjid Raya Baiturrahman. Hasil panen sawah—yang dikenal sebagai Oemong Sara—dipergunakan untuk menghidupi imam, khatib, dan bilal.
Karya kolonial Belanda, De Inrichting Van Het Atjehsche Staatsbestuur (1888) oleh K.F.H. Van Langen, bahkan menyebut secara detail bahwa sawah di Blang Padang dan Blang Punge dipersembahkan Sultan untuk masjid. Penjelasan itu diperkuat oleh Snouck Hurgronje, orientalis Belanda yang menjadi saksi sejarah Aceh.
“Ini bukan sekadar tanah kosong. Sejak awal, Blang Padang punya roh keagamaan. Ia lahir dari ikrar wakaf Sultan untuk syiar Islam,” ungkap Dr. HT. A. Dadek, SH, MH, sejarawan Aceh yang meneliti dokumen lama.
Dari Aloen-Aloen hingga Esplanade
Peta kolonial Belanda tahun 1875 dan 1915 mencatat Blang Padang sebagai aloen-aloen—lapangan pusat kerajaan. Tidak pernah sekalipun kawasan ini dicatat sebagai tanah militer. Di masa kolonial, masyarakat menyebutnya Esplanade Plein, ruang keramaian untuk pesta rakyat.
Pasca kemerdekaan, Blang Padang terus menjadi ruang publik. Tahun 1958, lapangan ini menjadi tuan rumah Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) pertama, lalu kembali digunakan untuk PKA II (1972) dan PKA III (1988). Pada 1981, seluruh mata bangsa tertuju ke Banda Aceh ketika Blang Padang menjadi arena MTQ Nasional ke-XII, yang kala itu disebut “Desah Arafah”.
“Blang Padang adalah memori kolektif warga Aceh. Dari kecil kami sudah main bola di sini, nonton tarian massal, bahkan ikut kampanye politik. Rasanya aneh kalau tiba-tiba disebut tanah wakaf,” kata Abdullah, 63 tahun, warga Peunayong yang sejak kecil bermain di lapangan itu.
Suara dari Pejabat dan Sejarawan
Bukan hanya rakyat, sejumlah pejabat lama Banda Aceh juga angkat bicara. Letkol (Purn) Teuku Oesman Jacoeb, wali kota Banda Aceh (1959–1967, 1970–1973), menegaskan bahwa Blang Padang bukan milik militer, melainkan lahan sipil.
Teuku Ali Basyah, sejarawan sekaligus mantan Kepala Kanwil Penerangan Aceh, menyebut Blang Padang sejak masa kolonial menjadi ruang hiburan rakyat. Bahkan, pemerintah kota kala itu memungut retribusi dari pedagang yang berjualan saat ada keramaian.
Sementara itu, mantan Kepala Kantor Pertanahan Banda Aceh, Drs. H. Teuku Sulaiman, MM, memastikan tidak ada hak apapun yang tercatat atas tanah Blang Padang di arsip pertanahan. “Artinya, statusnya tidak pernah berubah sejak era kesultanan: tanah wakaf,” ujarnya.
Pertarungan Status: Publik atau Wakaf?
Kini, perdebatan mengerucut pada dua posisi.
Pemerintah Kota menekankan fungsi Blang Padang sebagai ruang terbuka hijau, bahkan diatur dalam Qanun Tata Ruang Banda Aceh. Selama puluhan tahun, pemeliharaannya dibiayai APBK dan APBD.
Nazhir Masjid Raya Baiturrahman bersama ulama dan tokoh keturunan Sultan, menegaskan Blang Padang harus disertifikasi sebagai tanah wakaf.
Dukungan atas langkah sertifikasi datang dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, keturunan Sultan Iskandar Muda, pejabat syariat Islam, hingga mantan ketua Mahkamah Syar’iyyah Aceh. Mereka sudah menandatangani petisi bersama.
“Kalau Blang Punge saja sudah punya sertifikat wakaf, kenapa Blang Padang tidak? Sejarahnya sama, statusnya sama,” kata Ir. Tuwanku Muntazar, keturunan kesultanan Aceh.
Antara Hukum, Sejarah, dan Identitas
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa harta benda wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dialihkan. Artinya, jika Blang Padang resmi disertifikasi sebagai wakaf, maka seluruh pengelolaan akan tunduk pada nadzir Masjid Raya.
Namun, muncul pertanyaan besar: apakah fungsi ruang publik bisa tetap terjaga? Apakah masyarakat masih bebas menggunakan Blang Padang untuk olahraga, rekreasi, dan acara budaya?
Di sisi lain, isu ini juga menyentuh identitas Aceh. Bagi sebagian pihak, mengembalikan status wakaf berarti mengembalikan marwah Sultan Iskandar Muda dan memperkuat posisi Masjid Raya sebagai pusat peradaban. Bagi pihak lain, mempertahankan Blang Padang sebagai ruang publik adalah menjaga hak demokratis warga atas ruang kota.
Menanti Putusan Sejarah
Kini bola panas ada di tangan pemerintah, ulama, dan masyarakat. Sertifikasi wakaf sedang diproses, namun masa depan Blang Padang masih penuh tanda tanya.
Bagi Tgk. Faisal Ali, Ketua MPU Aceh, langkah ini jelas: “Ini tanah wakaf. Kewajiban kita adalah melindungi amanah Sultan.”
Sementara pegiat lingkungan khawatir, “Kalau pengelolaan berpindah, jangan sampai Blang Padang kehilangan fungsinya sebagai paru-paru kota.”
Di antara tarik-menarik kepentingan ini, satu hal pasti: Blang Padang lebih dari sekadar lapangan. Ia adalah saksi bisu perjalanan Aceh, dari kejayaan Sultan Iskandar Muda, masa kolonial, hingga era modern. Masa depannya akan menentukan bagaimana Aceh menyeimbangkan sejarah, syariat, dan kebutuhan warganya hari ini.